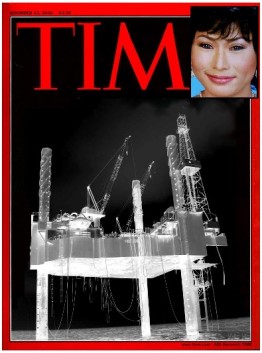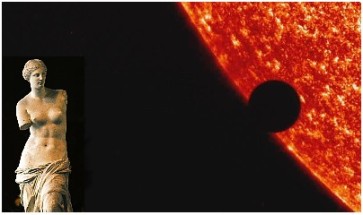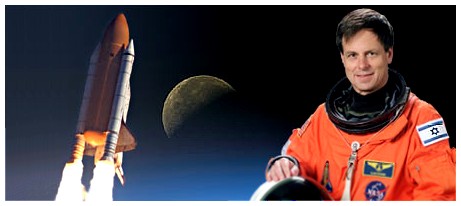PAK Haji marah besar. “Haram, lagu saya dibawakan Inul!” pekiknya berapi-api di depan kamera televisi. Ya, tampaknya Raja Dangdut Oma –yang menabahkan huruf R dan H sepulang dari Tanah Suci– Irama sangat teraganggu oleh putaran bor Inul, dan gemeletar tubuh Anisa Bahar saat berdangdut ria.
Semua orang tahulah. Gaya Inul dan Anisa tidak sekadar merunduk ke kiri, menengadah ke kanan, atau memutar dua tangan mirip gerakan menggulung benang layangan, seperti yang ditampilkan Pak Haji dalam klip Euforia. Inul dan Anisa mah werrrrrr!
Di mata Oma, eh Pak RH Oma, olah tubuh Inul yang muter bak gasing, dan getaran dada montok Anisa bahar yang seperti orang kesetrum itu amatlah mengumbar dan mengundang hasrat birahi. Dan, memancing birahi di depan umum itu haram. Haram! Titik.
“Penampilan mereka sudah mengarah kepada pendangkalan umat. Citra dangdut yang sudah dibangun, kembali terperosok masuk comberan,” ujar Oma yang lagu-lagunya selalu sarat dengan pesan moral dan religi.
Maka beramai-ramailah para musisi dan para pencipta lagu mengancam mencekal Inul dan Anisa. Mereka melarang dua perempuan itu membawakan lagu-lagu ciptaan mereka. Pak Haji juga mendesak stasiun televisi untuk segera menghentikan acara-acara dangdut yang dinilai mengeksploitasi hasrat birahi.
Dangdut memang identik dengan goyang, kata Oma, “tapi goyangan itu harus memiliki rujukan. Mau dibuat erotis atau artistik, tergantung pelakunya. Saya tidak rela lagu-lagu saya dinyanyikan mereka yang menceburkan dangdut ke dalam comberan,” kata Oma lagi.
Dia pasti betul. Erotis atau tidak Inul, juga tergantung kacamata yang digunakan penontonnya. Kalau dari sononya sudah menggunakan kacamata nge-seks, jangankan goyang Inul, penari kuda lumping pun bisa-bisa dianalogikan dengan (maaf…!) adegan sanggama.
Jika Pak Haji sempat menonton Duet Maut yang menampilkan Inul dan Ulfa Dwiyanti di SCTV, mungkin pandangannya akan sedikit berubah. Inul masih tetap dengan gayanya, memutar kencang bornya yang kenyal dan –pasti sangat– tumpul.
Pada saat yang sama, Ulfa sangat cerdik “memecah” kacamata para menonton sehinhgga sajian itu sama sekali tidak terasa erotik, apalagi ngeseks. Kesan yang muncul malah jadi sangat karikatural, kocak, dan cair.
Kami sekeluarga, termasuk anak-anak, menontonnya dan memperoleh kegembiraan, bukan rangsangan seksual, dari apa yang kata Oma cemoberan itu. Anak saya, lelaki, enam tahun, malah tergelak-gelak setiap Inul mulai memelinitir bor bundarnya.
“Kayak bayblade, pak!” serunya berulang-ulang. Di mata dia, putaran pinggul dan bokong itu lebih mirip ‘gasing modern’ yang saat itu digandrungi anak-anak. Dia sendiri punya tiga gasing model itu, warna-warni, yang sering diadunya dengan gasing teman-temannya di pekarangan.
Apa boleh buat, Sang Raja Dangdut telah bertitah. Bahwa titahnya itu mencerminkan pemaksaan kehendak terhadap orang lain tentulah harus jadi catatan pula. Pantas kalah orang sekaliber KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) marah betul sama RH Oma.
“Raja dangdut itu cuma julukan untuk. Bukan kekuasaan. Karena itu, Oma tidak bisa memerintahkan para penyanyi lain mengikuti kemauan dia. Dia dengan berlebihan telah meminta orang lain untuk mengubah ekspresinya. Siapapun yang membatasi kebebasan berekspresi seseorang harus kita lawan,” seru Gus Dur.
Tampaknya urusan ini memang seru. Buktinya, cuma perkara burit, kok sampai melibatkan seorang raja bo’ongan dan mantan presiden betulan harus ikut bicara. Cuma urusan bokong, kok sampai membuat para kiai dan ulama jumhur bermukabalah. Cuma urusan bokong kok sampai jadi topik liputan media internasional sekaliber Time dan BBC.
Saya yakin, Inul dan Anisa atau siapa pun yang mengikuti jejaknya, tak akan kandas hanya oleh pemberangusan yang sangat menyakitkan seperti itu.
Oma Irama sendiri pernah melakukannya dan berhasil. Dulu, ketika media televisi cuma ada satu-satunya, TVRI –yang kini kisruh terus itu– dia dicekal tampil. Toh Oma tak kalah akal. Buru-buru ia menyatakan masuk Golkar –sebelumnya jadi ikon PPP. Maka jelan ke layar televisi pun terbuka lebar.
Bahwa ketika kemudian peta politik berubah dan ia pindah lagi ke PPP, itu soal lain. Ketika masuk Golkar, ia bilang partai beringin berjanggut itu suah lebih islami. Logikanya, PPP kurang islami, dong. Ketika keluar dari Golkar dan masuk lagi ke PPP, boleh jadi ia beralasan PPP sudah lebih islami lagi.
Jadi, jika Inul cs dibungkam dan dilarang oleh orang-orang di jalur dangdut, pindah saja ke jalur rock, pop, keroncong, dan lain sebagainya.
Malah, siapa tahu ia bisa membangkitkan pula fenomena baru di jalur-jalur musik itu, sehingga yang muncul bukan lagi sekadar ‘ngebor’ tapi mungkin ngebom. Toh, Oma sendiri menciptakan trend baru dangdut setelah mengkolaborasi konsep sajiannya dengan rock. Dan itu sah-sah saja.
Sangat boleh jadi bor Inul memasuki babak kontroversi baru yang akan sangat panas, jika saja tidak ada insiden ledakan bom di Bandara Soekarno Hatta yang megalihkan perhatian pers dan publik. Soalnya, di tengah serunya orang berdebat (lagi) soal ngebor, tiba-tiba bom meledak.
“Low eksplosif, kok!” kata polisi. Entah low, entah high yang jelas perhatian publik sempat teralih ke sana. Apalagi korban luka berjatuhan, bahkan seorang perempuan muda bernama Yuli tiba-tiba kehialngan sebelah kaki.
Bayangkan, seorang perempuan pekerja –pengasuh bayi– tiba-tiba kehilangan kaki. Bagaimana ia akan bisa bekerja dengan baik? Bagaimana ia akan bisa membimbing bayi belajar jalan? Bagaimana dia akan mencari nafkah setelah itu?
Bom telah mengubah hidupnya, persis seperti ‘bor’ mengubah hidup Inul. Jika kereativitas –atau entah apa pun namanya– Inul diberangus, dipotong, dan dibatasi pencekalan, samalah artinya dengan Yuli –coba kalau namanya Iyul!– yang terpaksa diamputasi kakinya karena bom.
Di luar itu semua, dua peristiwa di atas –heboh bor dan bom– hanyalah makin menunjukkan bahwa selalu ada orang yang berusaha memaksakan kehedaknya kepada orang lain, tak peduli orang lain itu tersiksa dan tertindas seperti Inul atau bahkan celaka seperti Iyul, eh Yuli.
Sekian puluh tahun merdeka, ruapanya bangsa ini belum juga belajar dewasa. Kaciaaan…. deh.