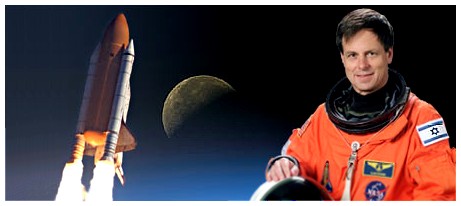DARAH mengalir dari lubang di dadanya. Menyebar merembesi bajunya bercampur debu padang pasir dalam ruap bau mesiu. Ia menggelepar sejenak. Mengejang. Lalu kaku.
Satu lagi hari itu nyawa melayang. Hassan Al Zaanin terlalu muda untuk mati. Tapi siapa peduli? Usianya baru 18. Siapa pula yang peduli, kecuali pencatat angka-angka korban konflik di Tepi Barat?
Dan, saban hari daftar korban tewas itu semakin panjang saja, seolah kematian tak berarti apa-apa. Sebelumnya, sudah lebih dari 5.000 remaja sebaya Zaanin kehilangan nyawa disambar kekejian peluru, roket, bahkan rudal, serdadu Israel.
Para remaja yang bertumbangan itu sebagian besar bukanlah para pemberontak dan orang-oran yang bergerak di bawah tanah untuk melawan kekuasaan Israel.
Jika pun mereka terlibat dalam intifadah, lebih karena terpaksa harus melawan –setidaknya mengusir– para serdadu Yahudi yang dengan keangkuhannya seolah merasa berkuasa atas seluruh jazirah Palestina. Keangkuhan yang kemudian membangkitkan perlawanan berlanjut dari bangsa Palestina.
Memang. Al Zaanin, bukanlah siapa-siapa. Hari itu di awal Juli di bawah terik sengangar di Beit Hanun, ia melihat gerilyawan garis keras Palestina memasang sebuah bom di tepi jalan untuk menghadang tentara Israel di Jalur Gaza.
Tentara Israel mengambil alih Beit Hanun setelah serangan roket para pejuang Palestina yang menewaskan dua orang di Israel selatan, tepat di seberang perbatasan. Dan, menyatakan akan menghancurkan gerilyawan garis keras di Beit Hanun.
Tentu saja para gerilyawan tak tinggal diam. Mereka menyiapkan penghadangan antara lain dengan memasangi bom di jalan-jalan yang diperkirakan akan dilintasi serdadu Yahudi. Namun warga tampaknya takut pengeboman di tepi jalan akan memicu serangan besar-besaran ke daerah yang diduduki kembali itu.
Hassan al‑Zaanin, bersama warga lain yang mungkin sudah bosan kekerasan, menyaksikan aksi penghadangan itu. Mereka melihat ketika sejumlah pria bersenjata memasang bom di tepi jalan, dan meminta itu untuk menghentikannya. Tentu saja permintaan itu ditolak.
Warga terus mendesak. Kaum gerilyawan tetap ngotot. Dua pihak yang sesungguhnya masih dalam satu kubu ini pun bersitegang, sampai para pria bersenjata itu melepaskan tembakan ke udara untuk mengusir warga. Dan, akhirnya menembak ke arah kerumunan.
Di situlah Zaanin. Ia tersungkur dengan dengan dada disarangi peluru. Ia tewas dalam perjalanan ke rumah sakit.
Zaanin bukanlah satu-satunya korban di pihak Palestina sejak perseteruan meletus kembali menyusul perangai Israel yang tetap memaksakan kehendaknya menguasai seluruh jazirah.
Sebelum Zaanin, ada 5.022 sebayanya telah gugur. Belum lagi 950-an madrasah hancur –dan 300 sekolah dijadikan markas militer Israel– sehingga 9.000-an pelajar tidak lagi dapat bersekolah.
Serdadu Yahudi juga menghancurkan 8.000 rumah, sehingga 70 ribu warga Palestina kehilangan tempat tinggal, sementara 26 ribu lagi warga cedera akibat kekerasan Zinonis.
Akibat lain –yang tak kalah mengerikan– adalah 3.000-an perempuan hamil terpaksa melakukan aborsi karena tidak memperoleh akses ke rumah sakit dari Israel, 40 persen dari 3 juta warga Palestina hanya makan sekali sehari dan 70 persen penduduk Palestina kehilangan lapangan pekerjaan.
Ya, Zaanin adalah salah satu korban, salah satu cermin tentang sosok yang terjepit di tengah konflik tak berkesudahan, karena masing-masing pihak tampaknya memang tidak ingin menyudahinya.
Ia juga menggambarkan bahwa di kalangan warga Palestina sendiri sudah berkembang pendapat untuk menyudahi saja kekerasan dalam mengekspresikan perlawanan terhadap musuh, dan mencari cara lain yang tidak terlalu mengalirkan darah warga sipil tak bersalah.
Jika di kalangan warga sipil biasa ada sosok seperti Zaanin, di tataran elite juga muncul berbagai organisasi dan faksi yang mulai menunjukkan pandangan berbeda, bahkan terkesan berseberangan satu sama lain, meski mereka tetap terikat pada satu tujuan utama: berjuang untuk memerdekakan Palestina.
Sebagai warga negara yang peduli dengan negaranya, seluruh warga Palestina harus terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, walaupun masing‑masing caranya berbeda. Bisa lewat militer, politik dan sosial.
Jika kaum radikal tetap memilih perlawanan bersenjata lewat gerilya, intifada, bahkan aksi bom bunuh diri, maka kelompok lain memilih cara yang berbeda pula. Melalui diplomasi, aksi-aksi sosial, gerakan dinta damai antarbangsa. Termasuk antara bangsa Palestina dan Yahudi sendiri, karena di antara bangsa Israel pun ada yang lebih mencintai perdamaian dan hidup rukun bersama tetangga Arab-nya.
Tapi, Israel di bawah Ariel Sharon adalah Yahudi dalam karakternya yang sejati. Ia justru seperti sengaja menghapus jejak-jejak semangat perdamaian yang dipancarkankan warganya, bahkan pernah juga digalang pada masa Rabin dan Peres.
Sharon telah menempatkan diri sebagai puncak kebenaran dan keadilan itu sendiri. Orang lain, bangsa lain, tidak. Karenaya, dia tak peduli seluruh bangsa mengutuknya.
Dia tak melihat kecaman marak di mana-mana. Sharon adalah Sharon. Baginya, dunia ini hanyalah Israel dan (pasti) Amerika yang seolah jadi bapak moyangnya, dan kalau perlu dibangkanginya pula.
Kegelisahan dunia internasional, terutama Bangsa Arab terbukti sudah. Sang Jenderal Haus Darah –demikian salah satu julukannya– telah menancapkan taringnya mencabik perdamaian dan merobek-robek rasa kemanusian banyak bangsa di dunia.
Lihat saja, bagaimana ia tak mempedulikan hasil pemungutan suara sidang darurat Majelis Umum PBB belum lama ini yang menunjukkan bahwa sebagian besar negara anggota PBB mendukung resolusi yang mengharuskan Israel mematuhi keputusan Pengadilan Internasional bahwa pembangunan tembok pengaman di Tepi Barat, Palestina, adalah ilegal. Artiya, Israel harus membongkar tembok itu dan segera memperbaiki segala kerusakan fisik yang terjadi.
Apa yang terjadi? Tentu saja atas dukungan penuh Amerika Serikat –celakanya ia punjya hak veto di PBB– Israel menentang resolusi tersebut. Boro-boro menghentikan dan membongkar beenteng, mereka malah melanjutkan pembangunannya.
Bayangkan, 150 negara yang mendukung resolusi itu, ternyata kalah ‘suara’ hanya oleh dua negara. Israel dan Amerika!
Mungkin betul kata Akram Adlouni, masalah Palestina, termasuk kemerdekaan negeri itu, sebenarnya bukan hanya milik rakyat Palestina dan urusan bangsa Arab. “Masalah Palestina adalah urusan umat Islam di seluruh dunia,” ujar Sekretaris Jenderal Yayasan Al-Quds yang berbasis di Beirut.
Ya. Dan –konon– lebih dari 90 persen penduduk Indonesia ini adalah muslim. Seperti Adlouni. Seperti Arafat.
Seperti juga Zaanin. ***
Bandung, 230804