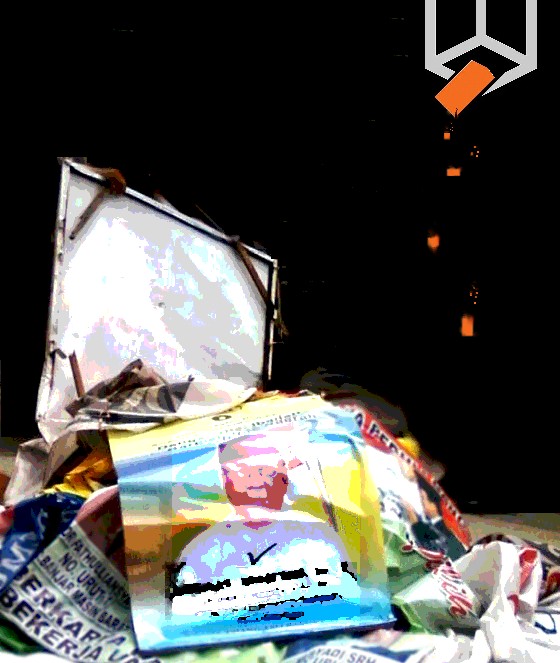DUNIA ini kayaknya tak seru kalau tak ada orang iseng. Iseng bisa dikatakan sebagai perbuatan tanpa tujuan yang jelas. Entah karena tak ada kerja lain, entah karena pembawaan. Namanya juga iseng, banyak orang tak begitu peduli. Padahal akibatnya bisa saja mengguncang dunia.
Contoh paling kecil, anak-anak berlomba melotar kerikil. Iseng dan sangat biasa. Tapi ketika mereka baku lontar itu di tepi jalan atau di tepi rel kereta api yang lalulintasnya sibuk, urusan bisa jadi lain. Berulangkali terjadi insiden kerikil menembgus kaca mobil yang melaju di jalan tol, atau menerobos jendela kereta yang sedang meluncur kencang.
Pernah terjadi, aksi iseng dua anak Medan. Mereka menerobos pagar bandar udara lalu ngumpet di dalam ruang roda –di dalam perut– pesawat yang sedang parkir.
Ujung-ujungnya, mereka terbawa terbang ribuan kilo meter hingga ke Jakarta. Untung tidak celaka. Tapi dunia jadi heboh, karena perbuatan mereka bisa membahayakan tidak saja diri mereka sendiri, tapi juga lebih seratus penumpang pesawat.
Seorang bocah belasan tahun di London, Inggris, sempat bikin geger dunia intelijen. Dari kamarnya, ia bermain komputer, masuk ke internet, lalu menjelajah dunia maya itu sampai kemudian masuk ke situs Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
Semula kalangan intelijen negara adidaya itu panik bak kebakaran jenggot sebab ternyata ada penyusup. Para agen disebar, jaringan internet ditelusuri. Mereka sendiri terperangah ketika menemukan penerobos itu bukan musuh yang berkepentingan dengan rahasia negara Amerika, melainkan ‘cuma’ anak ingusan.
Boleh jadi, pekerjaan orang iseng pula ketika pada April 2004 tampilan situs Tabulasi Nasional Pemilu Komisi Pemilihan Umum (TNP-KPU) tiba-tiba menampilkan gambar-gambar dan nama-nama aneh sebagai pengganti logo partai politik peserta pemilu.
Para pengakses http://tnp.kpu.go.id saat itu mungkin akan tertawa sendiri. Bayangkan, sejumlah partai barubah gambar dan nama.
Ada Partai Cucok Rowo, Partai Kelereng, Partai Kolor Ijo, Partai Jambu, Partai Mbah Jambon, Partai Dukun Beranak, Partai Wiro Sablenk, Partai Air Minum Kemasan Botol, Partai Dibenerin Dulu, dan Partai Jangan Marah Yaa.
Orang partai tentu bisa marah. Para peselancar internet mungkin mesem-mesem karena tahu bahwa itu perbuatan orang iseng yang sengaja ingin menggoda. Sedangkan orang yang biasa mengganggu situs orang lain, mungkin ngakak menikmati hasil perbuatannya.
Insiden itu bisa saja digolongkan pada perbuatan iseng. Tapi akibatnya sungguh luar biasa. Setidaknya, ia menunujukkan bahwa piranti canggih yang digunakan untuk membantu proses penghitungan suara pada pemilihan umum itu ternyata rentan gangguan.
Padahal negara telah mengeluarkan biaya –entah dari anggaran, entah dari bantuan asing– ratusan miliar. Padahal dana itu digunakan juga untuk menjamin keamanan dari sistem yang digunakan tersebut. Padahal, sejak awal sudah muncul polemik.
Insiden ini pun sebenarnya sekadar menegaskan bahwa tidak ada sistem buatan manusia yang sempurna. Sebelumnya, pihak KPU sendiri sudah yakni bahwa jaringan komputer mereka aman, sebab sekurang-kurangnya ada ‘tujuh benteng’ yang akan menghalangi orang-orang iseng menembus basis data mereka.
Tapi sebagaimana galibnya dalam dunia para hacker –yang lebih tepat sih cracker yaitu orang nyang suka keluar-masuk sistem dan men-delete atau menghancurkan apa saja– makin tinggi tingkat keamanan sebuah situs, makin menantang.
Begitu halnya dengan situs KPU. Tanda-tanda bahwa akan ada saja orang yang mengganggu, sudah sejak dini dikemukakan para pakar. RM Roy Suryo ahli telematika, dan Heru Nugroho yang di kalangan masyarakat teknologi informasi (TI) dijuluki “bapak asuh” para hacker, menyatakan TI Indonesia sedang dipertaruhkan dalam event Pemilu.
Gangguan mungkin saja dilakukan sekadar iseng tanpa motif politik tertentu. Mulai dari gangguan ringan seperti mengganti halaman, memasukkan gambar–mungkin gambar porno– sampai memodifikasi data. Dan, hal itu ternyata terjadi.
Dua hari setelah insiden “Partai Cucok Rowo dll” itu, koran tempat saya bekerja menerima surat elektronik dari seseorang yang memberi kesaksian bahwa pengganggu situs KPU betul-betul orang iseng, amatiran, sama sekali tak punya motif lain kecuali sekadar mengganggu.
“Orang itu hanya ingin membuktikan bahwa sistem yang dibangun Tim Tekonologi Informasi KPU tidak steril dan bisa dijebol, sehingga dunia tahu hasil pekerjaan yang menelan biaya ratusan miliar ini tak 100 persen aman,” kata sang pemberi info itu.
Wah, wah, wah, ternyata cuma iseng. Cuma ingin ‘menjajal’ para pakar yang dilibatkan dalam pengembangan sistem teknologi informasi oleh KPU. Padahal yang dikerjakan oleh para ahli yang dilibatkan KPU itu bukan kerja iseng, bukan sekadar membangun situs untuk senang-senang. Ini pekerjaan untuk melayani jutaan warga yang ingin segera tahu hasil pemilihan umum.
Bayangkan, untuk membangun jaringan itu, negara mengeluarkan dana sekitar Rp 154 miliar untuk komputer, ditambah Rp 27 miliar untuk telepon satelit, Rp 19 miliar untuk Telkom serta Rp 121 miliar untuk biaya pelatihan dan operatornya. Total investasi TI-KPU Rp 321 miliar.
Saya hanya bisa geleng-geleng kepala ketika diberitahu bahwa sang pengganggu itu betul-betul orang iseng. “Pelakunya itu boleh disebut pendatang baru di komunitas hacker, namanya tak pernah muncul. Ia orang Indonesia asli dan sekarang bersembunyi karena tak menyangka aksinya berdampak luar biasa,” tutur pemberi informasi itu lewat saluran telepon.
Ya, luar biasa. Ia membuktikan banyak hal terkait dengan pengembangan sistem teknologi informasi KPU, sekaligus mungkin juga sindiran pada para politisi kita yang sejak pecahnya reformasi begitu bergairah bikin partai.
Pemilihan umum telah membuktikan kepada partai-partai itu, seberapa besar pendukung mereka, dan seberapa banyak rakyat yang memilih mereka. Padahal, mereka mendirikan partai itu dengan sungguh-sungguh, tidak sekadar iseng karena tak ada kerjaan lain.
Atau? ***
Bandung, 190404